Layla
Die Stoffe, die uns tragen
Der Duft von neuem Stoff und Desinfektionsmittel lag in der Luft des Kaufhauses. Layla stand vor dem Tisch mit den Restposten, ihre Finger streiften sanft über den schweren Jersey eines schlichten grauen Kleides. Es war genau das, wonach sie gesucht hatte: dezent, langärmlig, preiswert. Ein zufriedenes Lächeln spielte um ihre Lippen.
„Entschuldigung, könnten Sie vielleicht…“ begann eine scharfe Stimme hinter ihr.
Layla drehte sich um. Vor ihr standen zwei Frauen, beide in ihren späten Zwanzigern, modisch in engen Jeans und blassweißen Sneakers, makellos geschminkt, die Haare in sorgfältigen Wellen. Die eine, eine Blondine, hielt bereits den Zeigefinger erhoben.
„Sie blockieren hier den ganzen Tisch“, fuhr sie fort. Ihre Begleiterin, eine Brünette mit strengem Pferdeschwanz, nickte energisch. „Man kann kaum rankommen. Und überhaupt –“ ihr Blick wanderte über Laylas hellrosafarbenes Kopftuch und den langen Mantel – „wenn man schon so viel Stoff braucht, sollte man vielleicht nicht den Sale-Bereich belagern.“
Laylas Gesicht behielt seinen freundlich neutralen Ausdruck. „Ich bin gleich fertig“, sagte sie ruhig auf Deutsch, mit nur leichtem Akzent, und wandte sich wieder den Waren zu. „Das Kleid hier ist perfekt.“
„Das? Das ist ja sackartig!“ Die Brünette lachte spitz. „Sofia, sieh mal. Total formlos.“
Sofia, die Blondine, musterte Layla nun mit einer Mischung aus Ärger und einer seltsamen Neugier. „Wissen Sie, wir meinen das gar nicht böse. Es ist nur… man integriert sich doch besser, wenn man sich auch anpasst. So etwas wie Ihr Kopftuch, das schürt doch nur Vorurteile.“
Layla nahm das graue Kleid vom Stapel. Ihr Gesicht war wie eine ruhige Wasseroberfläche, die die Steine der Unhöflichkeit einfach aufnahm, ohne Wellen zu werfen. „Dieser Stoff ist sehr hochwertig“, erwiderte sie, als hätte die Frau von Material und nicht von Integration gesprochen. „Er trägt sich gut und hält lange. Manchmal ist mehr Stoff auch mehr Wert.“
Sie wollte gehen, doch Sofia trat einen Schritt zur Seite und blockierte unauffällig den Weg. „Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Clara und ich arbeiten im Marketing, wir wissen, wie Wahrnehmung funktioniert. So wie Sie auftreten… das wirkt einfach verschlossen.“
In Laylas Augen blitzte etwas auf – nicht Ärger, sondern ein fast müdes Erkennen. Sie sah von einer zur anderen, diese beiden gepflegten Gesichter, erfüllt von der Gewissheit ihrer eigenen Richtigkeit. Plötzlich schien eine Entscheidung in ihr zu reifen.
„Wahrnehmung“, wiederholte sie leise. Dann, mit einer sanften, doch bestimmten Stimme: „Sie haben recht. Vielleicht sehen wir Dinge nur aus einer Perspektive. Meine Tante ist Stoffhändlerin. Sie sagt immer: Um einen Stoff wirklich zu verstehen, muss man ihn von beiden Seiten betrachten, die Webart spüren, die Faser kennen.“
Clara zog eine Augenbraue hoch. „Was hat das mit…“
„Ich fliege übermorgen zu meiner Familie nach Marokko“, unterbrach Layla sie, und ihre Worte kamen nun schneller, als folgte sie einem plötzlichen Impuls. „Geschäftlich, für meine Tante. Ich habe zwei Tickets. Meine Begleiterin ist erkrankt.“ Sie machte eine kleine Pause. „Sie könnten mitkommen. Eine Woche. Sie könnten sehen, woher… dieser Stoff kommt.“
Stille. Sofia und Clara tauschten einen ungläubigen Blick aus. Dann begann Clara zu lachen. „Sind Sie verrückt? Wir haben Jobs! Termine!“
„Ich biete Ihnen eine andere Perspektive an“, sagte Layla einfach. „Und vielleicht finden Sie auf dem Basar Stoffe, von denen Ihre Marketingabteilung nur träumen kann. Echte Handwerkskunst.“
Etwas in ihrer ruhigen Sicherheit ließ das Lachen von Clara verstummen. Sofia biss sich auf die Unterlippe. „Marokko… das ist doch recht sicher, oder?“
„So sicher wie jede Großstadt. Und ich kenne mich aus.“ Layla griff in ihre Tasche, zog zwei schlichte Visitenkarten heraus. „Hier. Denken Sie darüber nach. Mein Flug geht Donnerstag, 7 Uhr morgens. Falls Sie kommen: Terminal 2, Schalter 45.“
Sie ließ die Karten in Sofias überraschte Hand gleiten, nahm ihr graues Kleid und ging mit einem letzten, versöhnlichen Nicken davon. Ihre Ruhe wirkte wie ein unsichtbarer Mantel.
Donnerstag, 6:45 Uhr. Terminal 2. Layla, in einem praktischen Reise-Outfit und einem olivfarbenen Kopftuch, stand am Check-in-Schalter. Sie blickte nicht um sich. Entweder sie kamen oder nicht.
„Sie sind tatsächlich hier!“ Die Stimme klang atemlos. Hinter ihr standen Sofia und Clara, mit übergroßen Koffern und auffallend heller Freizeitkleidung. Beide wirkten nervös, aufgeregt und ein wenig übernächtigt.
„Wir haben Urlaub genommen“, erklärte Clara, als wolle sie sich selbst rechtfertigen. „Eine Chance für exotische Fotomotive. Für unseren Instagram-Account.“
Layla lächelte. „Willkommen. Bitte halten Sie Ihre Pässe bereit.“
Der Flug war unauffällig. Sofia und Clara blätterten durch Hochglanzmagazine über Marokko, voller Bilder von luxuriösen Riads und Sonnenuntergängen in der Wüste. Layla las ein Buch über textile Muster des Mittleren Ostens.
In Marrakesch angekommen, schlug ihnen eine Welle aus Hitze, Gerüchen und Geräuschen entgegen. Der Transfer zur Medina verlief chaotisch, das Taxi war klapprig, die Straßen überfüllt. Clara krümmte sich vor dem Fenster, als ein Motorrad mit drei Personen haarscharf vorbeischoss.
Die Unterkunft war nicht das erwartete Luxus-Hotel, sondern ein traditionelles Riad, versteckt in einem labyrinthischen Gässchen. Es war schön, aber einfach. „Wo ist der Pool?“ fragte Sofia enttäuscht, als ihnen der Besitzer, ein älterer Mann mit freundlichen Augen, ihren schmucklosen Hof zeigte.
„Der Pool ist die Teestunde auf der Terrasse“, antwortete Layla ruhig. „Und der Blick in den Himmel zwischen den Mauern.“
Am nächsten Morgen kündigte Layla an, sie würden auf den Souk gehen. „Ziehen Sie etwas an, das Schultern und Knie bedeckt. Und bringen Sie einen großen Schal mit.“
Proteste folgten. „Es sind 35 Grad!“ jammerte Clara in ihren Shorts und Tanktop.
„Der Schal ist für die Sonne. Und für den Respekt.“ Laylas Ton ließ keinen Widerspruch zu. Widerwillig zogen die beiden Frauen leichte Blusen und lange Hosen an.
Der Basar war eine Offenbarung und eine Überwältigung. Ein Strom aus Farben, Rufen, dem Duft von Gewürzen, Leder und Kameldung. Händler riefen sie an, Kinder liefen zwischen den Beinen hindurch, Eselskarren zwängten sich durch die Menge. Sofia und Clara klammerten sich aneinander, ihre Augen weit aufgerissen. Layla dagegen bewegte sich mit einer anmutigen Gelassenheit durch das Chaos, als wäre sie ein Teil dieser organischen Maschine.
Vor einem Stoffladen blieb sie stehen. Berge von Seide, Baumwolle, Leinen türmten sich darin. Ein älterer Händler mit einem verschmitzten Gesicht begrüßte sie mit ausgebreiteten Armen. „Layla! Tochter meiner Freundin! Willkommen!“
Sie wechselten freundschaftliche Begrüßungen auf Arabisch. Dann begann Layla, Stoffe zu mustern, fühlte sie zwischen den Fingern, hielt sie gegen das Licht. Sie verhandelte um einen Ballen indigoblauer handgewebter Baumwolle, ihr Deutsch wechselte fließend in Arabisch, ihre Gesten waren ruhig und bestimmt. Der Händler schien zu schimpfen, lachte dann und nannte einen neuen Preis. Layla lächelte, schüttelte den Kopf und nannte ihren. Schließlich einigten sie sich mit einem Händedruck.
„Das war beeindruckend“, murmelte Sofia, die kaum etwas verstanden hatte. „Aber er hat dich fast übers Ohr gehauen!“
„Das ist der Tanz“, sagte Layla. „Jeder muss sein Gesicht wahren. Der Anfangspreis ist nie ernst gemeint. Es geht um den Austausch, nicht nur um das Geschäft.“
Sie führte sie weiter, kaufte Arganöl, Datteln, kleine Keramikschalen. Immer verhandelte sie, immer mit derselben ruhigen Freundlichkeit. Langsam begannen Sofia und Clara zu begreifen, dass Laylas „Verschlossenheit“ in Wahrheit eine tiefe Vertrautheit mit den Codes dieser Welt war – Codes, die ihnen völlig fremd waren.
Der Wendepunkt kam am dritten Tag. Sie wollten eine historische Medersa besichtigen. Vor dem Eingang wies der Wächter barsch auf Clara, deren Bluse trotz der langen Ärmel einen Zentimeter zu tief ausgeschnitten war. „Nicht angemessen“, sagte er in gebrochenem Französisch. Ein kleines Publikum begann sich zu sammeln, Blicke wurden unangenehm intensiv.
Clara errötete vor Scham und Wut. „Das ist lächerlich!“
Layla trat vor. Ohne ein Wort nahm sie den großen Schal, den sie immer bei sich trug, und wickelte ihn kunstvoll um Claras Oberkörper und Kopf, sodass ihr Ausschnitt verdeckt wurde, das Ensemble aber fast wie eine modische Stola wirkte. „So“, sagte sie leise. „Jetzt sind wir alle angemessen.“
In dem Moment, als der schwere Stoff ihre Haare und Schultern bedeckte, geschah etwas Merkwürdiges mit Clara. Die aufgeregte Scham wich. Die neugierigen Blicke der Umstehenden prallten an der neuen Barriere ab. Sie fühlte sich nicht eingesperrt, sondern, zu ihrem eigenen Erstaunen, geschützt. Sie atmete tief durch. „Okay. Gehen wir.“
In der Medersa, in der Stille des Innenhofs mit seinem komplexen Mosaik, sprach Sofia leise zu Layla. „Das mit dem Schal… ist das immer so? Dass man sich beobachtet fühlt?“
Layla betrachtete eine Wand voller geometrischer Ornamente. „Man ist immer sichtbar. Als Frau, als Fremde, als Gast. Der Unterschied ist, ob man die Sichtbarkeit kontrollieren kann. Manchmal ist ein Schleier nicht ein Käfig, sondern ein Raum, den man selbst definiert. Er sagt: Du siehst nur, was ich dir zu sehen gebe.“
Die Worte hingen in der heißen Luft. Sofia sagte nichts, aber ihr Blick war nachdenklich geworden.
Am Abend, beim Tee auf der Riad-Terrasse, schlug Layla vor: „Morgen besuchen wir einen besonderen Markt außerhalb der Stadt. Für diesen Markt schlage ich vor, dass ihr beide etwas Traditionelleres anzieht. Es wird respektvoller aufgenommen und… einfacher für uns alle.“
„Traditioneller?“, fragte Clara misstrauisch.
„Ich habe zwei Abayas und Niqabs von meiner Tante hier. Sie sind leicht, luftig. Man wird euch in Ruhe lassen. Ihr könnt einfach… beobachten.“
Sofias erster Impuls war, abzulehnen. Doch die Erinnerung an die belastenden Blicke, an das Gefühl der Ausstellung am Vortag, war frisch. Und etwas in Laylas Vorschlag klang nicht wie eine Bevormundung, sondern wie ein Angebot für eine Waffenruhe. Ein Tag ohne bewertende Augen.
„Ein Experiment“, sagte Sofia schließlich, mit einem schiefen Lächeln zu Clara. „Für den Instagram-Account. ‚Verhüllte Perspektiven‘ oder so.“
Clara zögerte, dann zuckte sie mit den Schultern. „Warum nicht. Ein Tag im Kostüm.“
Als sie sich am nächsten Morgen ankleideten, war die Atmosphäre anfangs fast locker. Die schwarzen Abayas aus leichter Baumwolle waren tatsächlich angenehm kühl. Doch als sie die Niqabs anlegten – die Gesichtsschleier, die nur einen schmalen Schlitz für die Augen freiließen –, kam eine beklemmende Stille auf.
Die Welt schrumpfte auf einen Tunnelblick. Ihr Atem hallte leise in dem Stoff vor ihrem Mund wider. Die eigenen Geräusche wurden lauter, die der Außenwelt gedämpft. Als sie sich im Spiegel sahen, waren sie nicht wiederzuerkennen. Zwei anonyme, schwarze Gestalten.
„Ich fühle mich… unsichtbar“, flüsterte Clara, und ihre Stimme klang gedämpft und fremd.
„Nein“, korrigierte Layla sanft. Sie stand in ihrer gewohnten Kleidung, einem langen Kleid und einem hellen Kopftuch, daneben. „Ihr seid sichtbar als respektvolle Frauen. Aber euer Privates – eure Haut, eure Haare, eure unmittelbaren Reaktionen – die sind unsichtbar. Das ist der Unterschied.“
Der Markt lag in einer kleinen Stadt am Rande des Atlasgebirges. Er war weniger touristisch, ein Ort für den lokalen Bedarf. Und hier geschah die Verwandlung.
In ihren vollständigen Verhüllungen wurden Sofia und Clara nicht mehr angegafft, nicht mehr angesprochen, nicht mehr als Ziel für Händler oder neugierige Blicke auserkoren. Sie waren wie Geister, die durch die Menge glitten. Anfangs war es befremdlich, dann befreiend. Sie konnten die lebendigen Szenen beobachten, ohne selbst Teil der Szene zu sein: die Frauen, die gemeinsam lachten, die Männer, die ernsthaft über Schafpreise verhandelten, die Kinder, die zwischen den Ständen spielten.
Layla führte sie zu einem Stoffhändler, einem Mann mit einem weisen Gesicht und ruhigen Händen. Hier sollte das eigentliche Geschäft stattfinden. Sie stellte ihre beiden Begleiterinnen vor als „geschätzte Geschäftspartnerinnen aus Europa, die die Qualität unserer Stoffe schätzen lernen“. Der Händler nickte ihnen ernst zu, ohne Anflug von Aufdringlichkeit.
Dann begann Layla zu verhandeln. Nicht um ein Kleid, sondern um eine ganze Kollektion handgewebter Decken für ein europäisches Modelabel, das Sofia und Clara tatsächlich kannten. Die Zahlen, die flogen, waren beträchtlich. Laylas Stimme war die ganze Zeit ruhig, freundlich, aber von einem eisernen Kern durchzogen. Sie zitierte Webtechniken, Faserherkunft, den Zeitaufwand. Der Händler argumentierte mit Seltenheit und Familientradition.
Sofia und Clara standen reglos da. Durch die schmalen Sehschlitze ihrer Niqabs sahen sie nur Layla – wie sie da stand, die Verkörperung von Kompetenz und Respekt in dieser Welt, die sie, die „modernen“ Frauen, bisher nur als Kulisse für ihre Abenteuer gesehen hatten. Sie verstanden plötzlich, dass die Frau, die sie im Sale-Bereich belächelt und belehrt hatten, hier eine Macht war. Eine Brücke zwischen Welten. Und sie, in ihren schwarzen Hüllen, waren stumme Schülerinnen in ihrem Schatten.
Die Verhandlung zog sich hin. Die Sonne stand hoch. Unter ihren Abayas begannen sie zu schwitzen. Die anfängliche Befreiung schlug langsam in ein Gefühl der Abhängigkeit um. Sie konnten nichts sagen, nichts tun. Sie waren vollständig auf Layla angewiesen. Und in dieser Abhängigkeit wuchs etwas Neues: Demut. Und ein schmerzhaft klares Verständnis dafür, wie oberflächlich ihr eigenes Urteil im Kaufhaus gewesen war.
Schließlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, war ein Deal gemacht. Händedruck. Lächeln. Der Händler bot Tee an.
Als sie in einer ruhigen Ecke des Marktes saßen, die dampfenden Gläser vor sich, sprach Layla leise zu ihnen. „Jetzt versteht ihr vielleicht. Diese Kleidung“, sie deutete auf ihre eigene, „ist meine Entscheidung. Sie verbindet mich mit meiner Familie, meinem Glauben, meiner Kultur. Sie ist nicht weniger frei als Ihre Jeans. Sie ist nur anders frei. Im Westen bedeutet Freiheit oft, alles zeigen zu dürfen. Hier kann Freiheit auch bedeuten, etwas für sich behalten zu dürfen.“
Sie nahm einen Schluck Tee. „Ihr habt heute die Freiheit der Unsichtbarkeit erlebt. Und die Macht der Sichtbarkeit auf meine Art gesehen.“
Clara, ihre Stimme noch immer durch den Stoff gedämpft, sagte: „Es ist… anstrengend. So zu sein.“
„Ja“, gab Layla zu. „Manchmal ist es das. So wie es anstrengend sein kann, immer perfekt gestylt und bewertet zu sein. Jede Wahl hat ihren Preis.“
Am letzten Tag ihres Aufenthalts, auf dem großen Haupt-Basar von Marrakesch, spielte sich die finale Szene ab. Layla hatte eine letzte Verhandlung für ihre Tante zu führen, um seltene Seidenfäden. Sofia und Clara, die inzwischen ihre eigenen, weniger umhüllenden aber dennoch respektvollen Kleider trugen, begleiteten sie.
Vor dem Stand des Händlers jedoch überraschte Layla sie. Sie zog zwei Bündel aus ihrer großen Tasche. Es waren die beiden schwarzen Abayas und Niqabs vom Vortag.
„Für heute“, sagte sie mit ihrem freundlich neutralen Gesichtsausdruck, „würde ich vorschlagen, dass ihr diese wieder anlegt. Dieser Händler ist sehr traditionell. Er wird mit mir, einer alleinstehenden Frau, nur unter bestimmten Bedingungen verhandeln. Wenn ihr als meine… Schwestern auftretet, unter unserem Schutz, wird er es als Zeichen des Respekts sehen. Es wird den Weg ebnen.“
Es war keine Forderung. Es war eine Tatsache. Und nach den Erfahrungen der letzten Tage gab es keinen Protest mehr. Schweigend, mit einer neuen, fast zeremoniellen Ernsthaftigkeit, halfen sich die Frauen gegenseitig, die schwarzen Gewänder anzulegen. Der Stoff fiel vertraut über sie hinweg, verschluckte ihre Konturen, ihre Individualität. Sie wurden wieder zu den zwei anonymen, schwarzen Gestalten.
Layla stand vor ihnen, in ihrem sandfarbenen Kleid und dem kupferfarbenen Kopftuch, ihr Gesicht zufrieden, versöhnlich und freundlich neutral. So, wie sie im Kaufhaus gestanden hatte. Nur dass die Machtverhältnisse sich umgekehrt hatten. Sie war der Anker. Sie war die Führerin.
„Folgt mir“, sagte sie ruhig.
Sie traten an den Stand. Der Händler, ein ernster Mann mit grauem Bart, musterte die Gruppe. Seine Augen blieben auf Layla haften, nickten dann anerkennend, als er die beiden verschleierten Frauen hinter ihr sah. Die Verhandlung begann.
Layla verhandelte ruhig und bestimmt. Sie zeigte Musterbücher, diskutierte Farbbeständigkeit, Lotgrößen. Ihre Stimme war melodisch, aber unnachgiebig. Sofia und Clara standen schweigend und vollverschleiert hinter ihr. Sie beobachteten durch ihre Sehschlitze, wie diese Frau, die sie einst für unterdrückt und rückständig gehalten hatten, souverän eine geschäftliche Welt navigierte, die ihnen völlig verschlossen war.
Sie hörten den Respekt in der Stimme des Händlers. Sie sahen, wie sich zwei Welten auf Augenhöhe begegneten – durch Layla. Und in ihrem Schweigen, in ihrer freiwilligen Verhüllung, war keine Demütigung, sondern eine tiefe Lektion. Sie verstanden endlich, dass wahre Autorität nicht von der Kleidung kommt, die man trägt, sondern von einer inneren Wahrhaftigkeit und dem Wissen um den Wert dessen, was hinter den Oberflächen der Welt verborgen bleibt.
Der Handel wurde besiegelt. Als sie sich vom Stand entfernten, blieb Layla einen Moment stehen und wandte sich halb zu ihren Begleiterinnen um. Ihr Gesicht war immer noch ruhig, aber in ihren Augen stand ein warmes Licht.
„Danke“, sagte sie einfach. „Für euren Respekt.“
Auf dem Rückflug schwiegen Sofia und Clara lange. Die Hochglanzmagazine blieben unberührt in der Ablage. Als das Flugzeug über den Alpen kreiste, sagte Sofia leise: „Ich werde nie wieder jemanden anhand seiner Kleidung beurteilen.“
Clara nickte. „Ich habe gedacht, wir würden ihr unsere Welt zeigen. Dabei hat sie uns ihre gezeigt. Und sie ist so viel komplexer.“
Sie blickten nach vorn, wo Layla schlief, ihr Kopf leicht an die Fensterscheibe gelehnt, ihr Kopftuch ein sanfter Schatten im gedimmten Licht der Kabine. Sie sah aus wie am ersten Tag: zufrieden, versöhnlich, freundlich neutral. Doch für die beiden Frauen hinter ihr war sie nicht mehr die Unbekannte im Sale-Bereich. Sie war die Frau, die sie durch einen Spiegel in eine andere Welt geführt hatte – eine Welt, in der ein Stoff nie nur ein Stoff ist, sondern ein Zeichen, ein Schutz, eine Sprache und manchmal eine Brücke.
](https://files.transmom.love/yurige-pt2/asellus.jpeg) Zozma, from SaGa Frontier (PS1): “Surely the fact that you are so devastated only shows how much you love the Princess?” Asellus: “Yes… as a friend! She was like a sister to me!” Denial is a hell of a drug—but Zozma won’t be having any of it…
Zozma, from SaGa Frontier (PS1): “Surely the fact that you are so devastated only shows how much you love the Princess?” Asellus: “Yes… as a friend! She was like a sister to me!” Denial is a hell of a drug—but Zozma won’t be having any of it… This exceedingly provocative illustration of Asellus and White Rose was not drawn for the SaGa Frontier game itself, but it is official artwork in later gatcha card games like Emperor's SaGa (2012). This is symbolic of Square-Enix's have-its-cake-and-eat-it-too queerbaiting attitude to the lesbian characters; at the same time as it denies or effaces the original game's more-than-subtextual relationship in strategy guides and public statements, it also sells artwork like the above, or adds sapphic fanservice to the remaster, or does stuff like
This exceedingly provocative illustration of Asellus and White Rose was not drawn for the SaGa Frontier game itself, but it is official artwork in later gatcha card games like Emperor's SaGa (2012). This is symbolic of Square-Enix's have-its-cake-and-eat-it-too queerbaiting attitude to the lesbian characters; at the same time as it denies or effaces the original game's more-than-subtextual relationship in strategy guides and public statements, it also sells artwork like the above, or adds sapphic fanservice to the remaster, or does stuff like 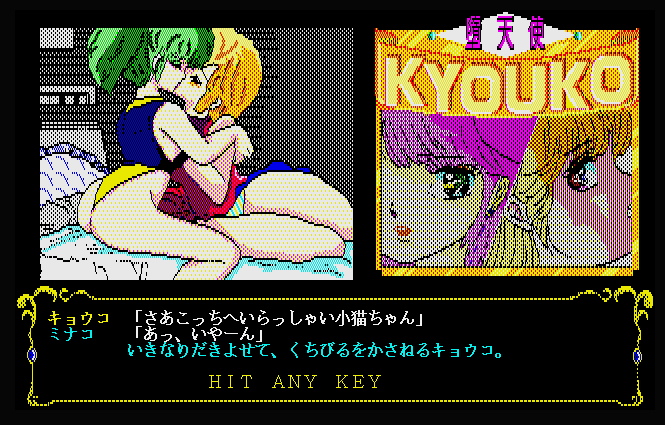 Kyōko: “Here here, kitten, come…” (Datenshi Kyōko, 1988).
Kyōko: “Here here, kitten, come…” (Datenshi Kyōko, 1988).